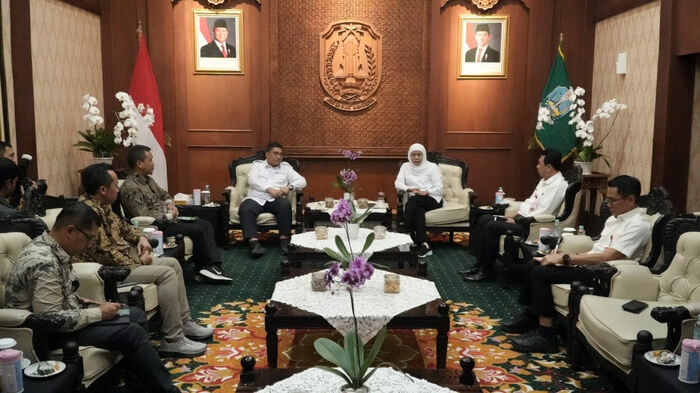MutiaraindoTv.My.Id | Jakarta, Minggu, 21 Desember 2025. –Kepemilikan P3MI hari ini berada dalam tekanan yang semakin kompleks.
Di satu sisi, ada upaya menaikkan deposito jaminan yang dibebankan kepada perusahaan penempatan.
Kebijakan ini diklaim sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan memastikan keseriusan pelaku usaha.
Namun di sisi lain, pemerintah justru semakin masif memperluas penempatan pekerja migran melalui skema G to G (Government to Government).
Skema ini, dalam praktiknya, menawarkan biaya yang jauh lebih murah karena ditopang langsung oleh negara.
Ketika swasta diposisikan untuk berkompetisi dengan pemerintah di sektor yang sama, maka hasil akhirnya nyaris pasti : pemerintah menjadi pemenang, bukan karena efisiensi murni, melainkan karena keunggulan struktural biaya.
Tekanan terhadap P3MI tidak berhenti di situ.
Biaya ENJAS Saudi sebagai sistem resmi penempatan ke Arab Saudi terus mengalami kenaikan.
Kenaikan ini tidak dibarengi dengan transparansi perhitungan, skema insentif, ataupun perlindungan margin bagi P3MI. Akibatnya, perusahaan penempatan terjepit dari dua arah sekaligus :
Dari dalam negeri oleh upaya kenaikan deposito dan regulasi berlapis,
Dan dari luar negeri oleh biaya sistem penempatan yang terus meningkat.
Dalam situasi seperti ini, pertanyaan mendasarnya menjadi sangat relevan:
Apakah negara masih memosisikan swasta sebagai mitra strategis, atau justru sebagai pihak yang secara perlahan disingkirkan?
Ketimpangan kebijakan ini juga berdampak pada dinamika internal organisasi pengusaha penempatan, khususnya APJATI.
Perebutan posisi Ketua APJATI semakin mengeras, karena jabatan tersebut kini dipandang sebagai alat tawar politik dan akses langsung ke pengambil kebijakan.
Organisasi yang seharusnya menjadi ruang advokasi kolektif berubah menjadi arena kepentingan, sementara substansi perjuangan industri justru terpinggirkan.
Ketika P3MI saling berhadapan satu sama lain, posisi tawar terhadap negara melemah.
Pada saat yang sama, negara tetap melaju dengan kebijakan yang menekan dari berbagai sisi.
Kombinasi ini menciptakan tekanan sistemik yang berbahaya dan berpotensi mendorong lahirnya praktik-praktik “kreatif” yang justru ingin dicegah oleh regulasi.
Sudah semestinya pemerintah kembali ke peran utamanya sebagai regulator, bukan pemain.
Negara perlu fokus pada penetapan standar, pengawasan yang konsisten, serta penegakan hukum yang adil.
Penempatan seharusnya dijalankan oleh pelaku usaha yang diawasi secara ketat, bukan oleh negara yang sekaligus menjadi kompetitor.
Jika arah kebijakan ini terus dibiarkan, maka P3MI bukan hanya menghadapi risiko bisnis, tetapi juga ancaman eksistensial.
Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya perusahaan penempatan, melainkan ekosistem perlindungan pekerja migran itu sendiri.
Paradoks Keunggulan Tenaga Kerja Indonesia
Pada masa lalu, tenaga kerja dari Cina dan Vietnam menjadi pesaing utama tenaga kerja Indonesia di berbagai negara tujuan.
Mereka dikenal disiplin, terampil, dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih baik.
Namun hari ini, peta persaingan itu berubah.
Tenaga kerja Indonesia justru menjadi yang paling diminati, bahkan dalam banyak kasus menjadi pilihan utama dan satu-satunya.
Keunggulan ini bukan semata karena keterampilan teknis. Daya tarik utama tenaga kerja Indonesia terletak pada fleksibilitas dan kepatuhan.
Mereka bersedia mengerjakan banyak jenis pekerjaan, sering kali melampaui batas yang tertulis dalam perjanjian kerja.
Sikap penurut, jarang membantah, dan cenderung menerima kondisi kerja apa adanya menjadikan mereka dianggap “mudah diatur” oleh pemberi kerja.
Namun di balik keunggulan pasar tersebut, tersembunyi sebuah ironi sosial.
Kepatuhan yang berlebihan ini tidak lahir dari sistem ketenagakerjaan yang sehat, melainkan berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan tenaga kerja Indonesia yang relatif rendah.
Ketika pilihan hidup terbatas dan daya tawar minim, kepatuhan menjadi strategi bertahan.
Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintah dengan lantang menyatakan kebijakan wajib belajar 12 tahun.
Kata “wajib” seharusnya mengandung makna kehadiran negara secara aktif, bukan sekadar pembebasan biaya pendidikan.
Wajib belajar berarti negara wajib mengawasi, wajib memastikan, dan wajib mencegah anak usia sekolah terlepas dari sistem pendidikan.
Realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Masih banyak anak usia sekolah yang berkeliaran, bekerja, atau putus sekolah dengan berbagai alasan ekonomi, keluarga, hingga pembiaran struktural.
Negara hadir dalam regulasi, tetapi absen dalam pengawasan.
Akibatnya, lahirlah generasi pekerja yang kuat secara fisik namun lemah secara posisi tawar.
Dengan demikian, keunggulan tenaga kerja Indonesia di pasar global hari ini sesungguhnya menyimpan paradoks.
Mereka unggul karena kepatuhan, tetapi kepatuhan itu lahir dari ketimpangan pendidikan.
Mereka diminati karena fleksibel, tetapi fleksibilitas itu sering berarti kerentanan terhadap eksploitasi.
Jika pemerintah ingin tenaga kerja Indonesia unggul secara bermartabat, maka kebijakan wajib belajar tidak boleh berhenti pada slogan dan anggaran.
Pengawasan aktif terhadap anak usia sekolah adalah kunci.
Tanpa itu, Indonesia akan terus mengekspor tenaga kerja yang unggul secara kuantitas, tetapi rapuh secara kualitas dan perlindungan.
Editor : Tikno